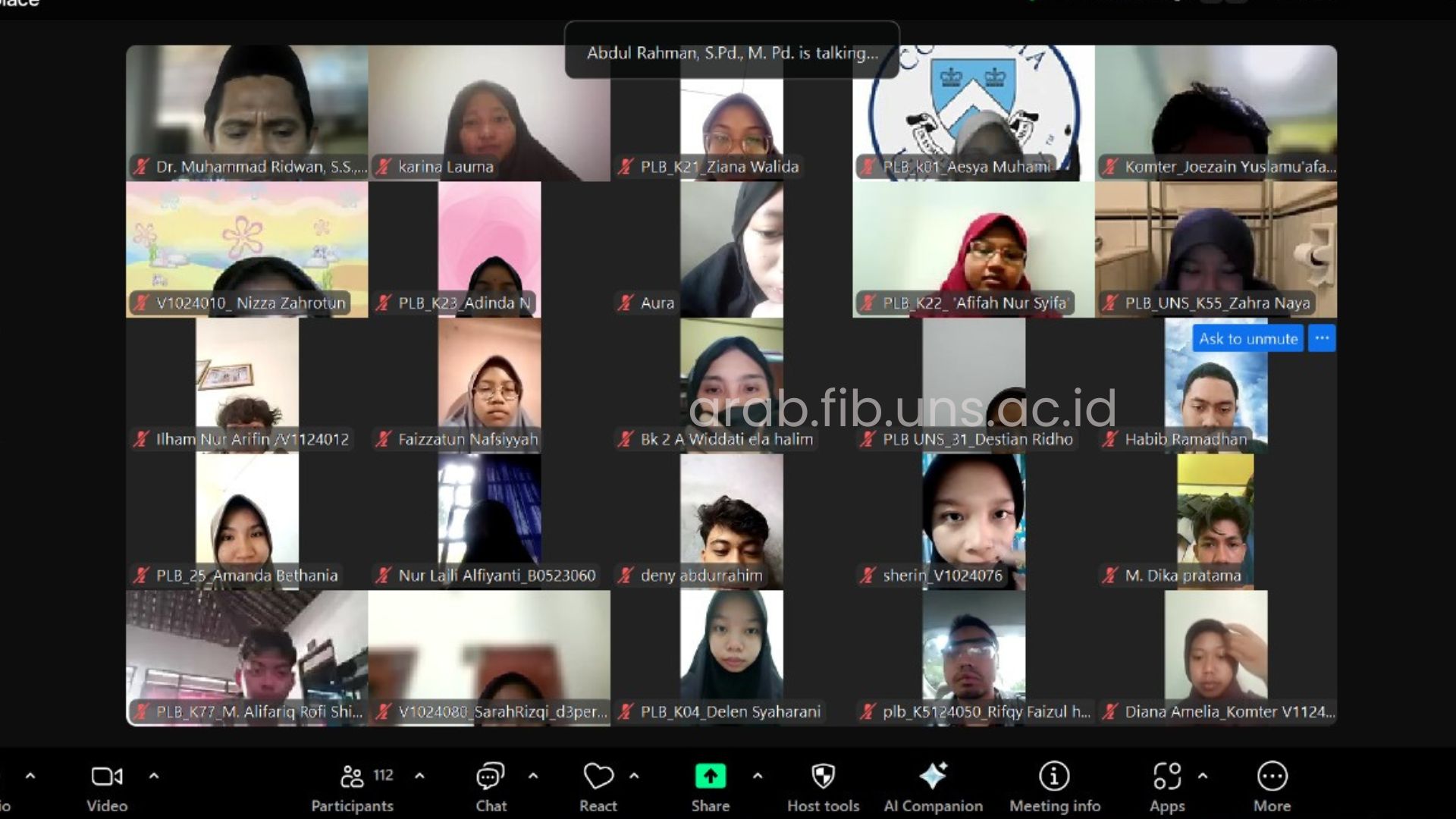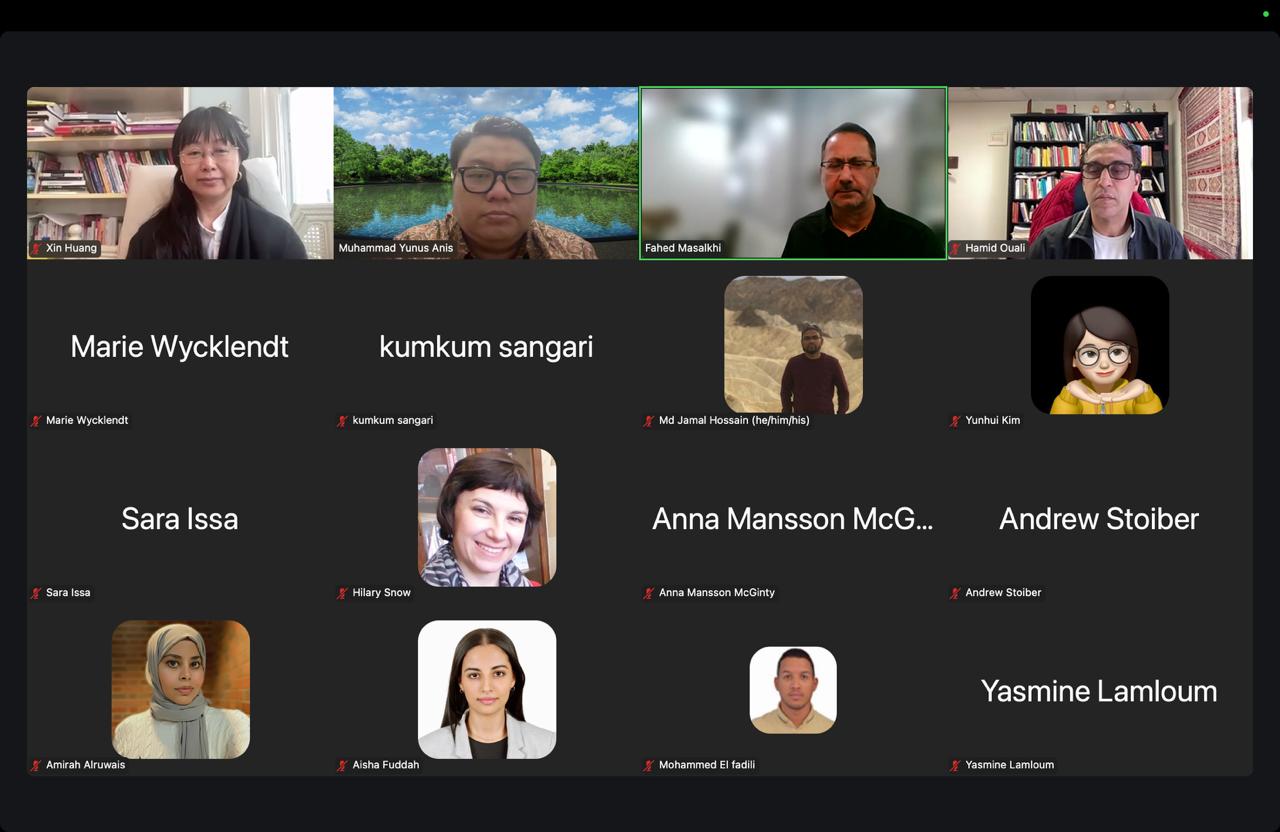“Tak pernah ada negara runtuh karena kelebihan pangan. Tapi sejarah berkali-kali membuktikan: kelaparan sanggup meruntuhkan peradaban.” – Soekarno
Ketika berbicara tentang nasionalisme, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada bendera, lagu kebangsaan, atau pengorbanan para pahlawan. Namun, siapa sangka bahwa nasionalisme juga bisa dimulai dari tempat sederhana yang akrab bagi kita semua, yakni meja makan.
Dr. Muhammad Ridwan, S.S., M.A., dosen Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret, menegaskannya lewat artikelnya berjudul “Mati dan Hidup dari Meja Makan: Saat Nasi Jadi Soal Negara” dan salah satu kuliah umumnya bertajuk Sedaring Episode #1. Ia berpendapat bahwa makanan bukan hanya soal isi perut, tetapi juga menyangkut martabat dan kedaulatan bangsa. Ketika pangan menjadi barang impor dan petani lokal tidak mampu bersaing, maka sesungguhnya bangsa Indonesia sedang kehilangan kedaulatannya. Padahal, pangan adalah isu strategis yang sejak lama menjadi perhatian para pemimpin Nusantara. Sultan Agung Mataram memahami bahwa serangan militer ke Batavia tak akan berhasil tanpa jaminan logistik, yang ia realisasikan dengan memenuhi lumbung padi. Begitu pula dengan Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Iskandar Muda yang masing-masing telah membangun sistem pangan sebagai pondasi kekuasaan dan keberlangsungan hidup rakyatnya.
Lalu, bagaimana dengan kita hari ini?
Urusan pangan hanya dianggap milik kebutuhan rumah tangga dan bukan tanggung jawab negara. Sawah-sawah mulai ditinggalkan seiring dengan menuanya para petani. Generasi muda tak sudi melirik cangkul. Impor diputuskan dengan mudah sementara pasokan pangan global pun sedang mengalami masa krisis. Bangsa kian melupakan petuah nenek moyang, “nandur sing dipangan, mangan sing ditandur” (menanam yang dimakan dan memakan apa yang ditanam). Ini bukan sekedar petuah bertani atau dongeng, namun ini adalah cara berpikir untuk hidup dia atas kaki sendiri. “Jika nasi di piring kita berasal dari beras impor, maka sebenarnya kita sedang memberi makan ekonomi bangsa lain,” ujar Ridwan.
Tantangan ini bukan hanya urusan petani. Kini, sudah waktunya bangsa ini berbenah diri. Tidak hanya menunggu kebijakan negara, namun pola pikir masyarakat juga perlu perubahan. Meja makan seharusnya menjadi tempat awal pendidikan nasionalisme: mengenal makanan lokal, menghargai kerja petani, memilih produk negeri sendiri, serta membangun kesadaran bahwa ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama.
Apa yang harus dilakukan?
Menghadapi tantangan ini, solusi bukan hanya bertumpu pada kebijakan negara, tetapi juga pada perubahan pola pikir masyarakat. Meja makan seharusnya menjadi tempat awal pendidikan nasionalisme: mengenal makanan lokal, menghargai kerja petani, memilih produk negeri sendiri, serta membangun kesadaran bahwa ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Langkah kecil seperti memilih beras dari petani lokal, mengenalkan anak pada masakan tradisional, dan menanam tanaman di pekarangan bisa menjadi kontribusi nyata.
Sejarah mencatat, bangsa yang kehilangan kendali atas pangannya akan kehilangan kendali atas nasibnya. Oleh sebab itu, penting bagi setiap keluarga untuk kembali melihat meja makan bukan sekadar tempat makan bersama, tetapi juga medan juang untuk masa depan bangsa. Sebagaimana Bung Karno memperingatkan bahwa “urusan perut adalah urusan hidup mati”, maka setiap sendok nasi yang kita suapkan hari ini adalah bagian dari keputusan besar: apakah kita ingin tetap merdeka atau hanya menjadi pasar dari bangsa lain. [mya]